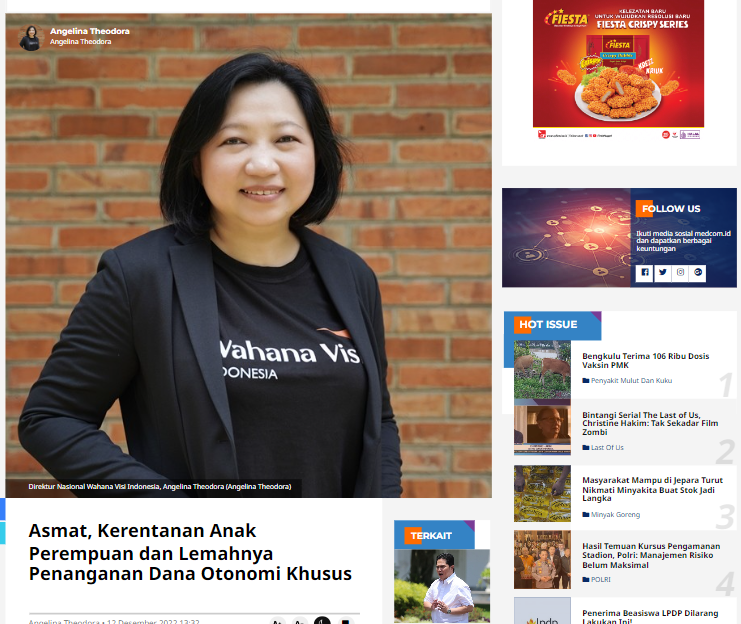Di Tapal Batas

Pengujung Agustus 2023. Dari jendela pesawat yang memusing di langit Pontianak, saya mengintip ke bawah. Hutan hijau, asap pembakaran yang mengepul, lahan perkebunan bergaris-garis, sungai-sungai lebar yang berwarna coklat bagai seekor naga yang mengibaskan ekornya ke laut lepas. Di antara lahan luas yang samar ditutupi asap asap pembakaran itulah, kota di lintasan khatulistiwa, Pontianak, berdiri dengan segala bangunan, plaza dan gedung-gedungnya yang menampilkan wujud dari sebuah kota mapan di negara berkembang.
“Tidak hanya asap pembakaran lahan yang terjadi sepanjang tahun dan seakan telah menjadi hal biasa. Tapi, banyak masalah lain,” kata Darso, supir yang mengantar saya meninggalkan Pontianak menuju Kabupaten Sambas dan kampung-kampung di bagian utara Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negeri tetangga, Malaysia. Lima jam kami berkendara, menyusuri perkebunan luas, jalan-jalan berdebu. Masalah apa lagi, bukankah perkebunan dan pertambangan itu telah membawa dampak yang baik? Darso hanya diam saja dan terus menyetir.
Sejak 2020 silam, media-media melaporkan angka kekerasan seksual yang tinggi terhadap anak. Inikah masalah selain kebakaran lahan? kumparan.com misalnya, merilis Sambas sebagai daerah yang mendominasi angka kekerasan seksual di Kalbar. Tidak hanya sampai di sana. Pernikahan usia dini, perdagangan anak, hingga stunting. Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2023 mencatat sebesar 30,5 persen kasus stunting di sini. Kenapa bisa?
Pagi baru dimulai, perempuan-perempuan membawa bakul cucian ke pinggir Sungai Sambas yang keruh tempat mereka mencuci dan mandi sekaligus buang hajat. Saat beberapa lelaki berangkat ke ladang mereka menggunakan sampan kecil, saya duduk di tepi Sungai Sambar yang kusam bersama lamunan. Sebagai daerah yang jauh dari Jakarta, kabar tentang daerah-daerah di pinggir, apalagi di batas negara seperti Sambas ini, tentu jarang terdengar. Apa yang terjadi di perkampungan-perkampungan yang jauh dari ibu kota selain hutan yang hilang saban tahun, korporasi besar yang mengeruk untung, serta capaian-capain pembangunan? Tapi, kekerasan seksual yang tinggi, angka pendidikan yang rendah—bagaimana bisa semua terjadi tahun ke tahun, bukankah pertambangan dan perkebunan yang luas telah mengangkat derajat masyarakat di sini menjadi terididik dan tidak lagi miskin? Apa yang salah?
Di Sambas, saya melipir ke Kantor Bupati, barangkali saya mendapatkan hal-hal yang lebih terang dari pada yang saya baca di media-media dengan segala keterbatasannya. Bupati sedang tidak bisa ditemui. Akan tetapi, di sebuah ruang rapat, kepala-kepala dinas kabupaten itu tengah berkumpul.
“Sejak Januari hingga Agustus 2023 ini, telah dilaporkan 65 kasus kekerasan terhadap anak. Rata-rata adalah kekerasan seksual. Ada 133 pasang ingin menikah muda Jumat kemaren. 90 persen dari mereka sedang hamil, lainnya sudah berhubungan. Artinya akan melahirkan 133 anak yang kemungkinan akan stunting. Sebulan bisa 300 perceraian. Pada 2022 saja, dari 65 jumlah aduan yang masuk mengenai kasus kekerasan terhadap anak, 43 di antaranya adalah kasus kekerasan seksual,” Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB—betapa rumitnya singkatan ini) Sambas, Fatma Aghitsni membeberkan data dengan gamblang dan wajah penuh kuatir.
Menurut Fatma, anak korban kekerasan tidak diasuh oleh orangtua. Ditambah lagi, indeks pembangunan manusia yang rendah—dengan bahasa lebih terangnya adalah tidak terdidik, itulah penyebabnya.
“Rata-rata tamat SD, ini masalah di Sambas,” kata Kepala Dinas Pendidikan Sambas Sumekto Hadi Suseno. Lantas, kenapa itu semua bisa terjadi? Bukankah daerah-daerah di pinggiran Indonesia ini adalah juga daerah yang berpaut erat pada adat dengan segala aturan hukumnya yang begitu mengikat untuk hal-hal yang sangat tak patut tersebut?
Saya berkendara makin ke utara Provinsi Kalimantan Barat. Di Sajingan Besar, perkampungan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, saya bertemu Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Sajingan Besar bernama Libertus.
“Instan! Pola pikir instan! Bukan adat yang salah! Media terlalu cepat datang. Film porno datang,” Libertus membuka mulutnya menjawab pertanyaan saya. Ia menerangkan lebih panjang tentang bagaimana masyarakat Dayak di kampung-kampung yang berbatasan dengan negara lain, tentang hutan adat yang kian menciut, tentang tempat sakral yang telah dimasuki alat berat dan segera beralih fungsi, tentang perusahaan-perusahaan besar yang telah menjadikan Kalimantan berubah menjadi lahan-lahan industri.
“Dulu, apa saja ada. Ikan ada. Hutan, lahan, semua ada. Dan sekarang? Apa yang dimiliki orang Dayak? Perusahaan bermitra dengan masyarakat, akan memberi CSR, plasma, itu semua janji palsu!” Lalu Libertus diam. Dipalingkan mukanya ke halaman datar di belakang rumahnya, tempat ia menanam berbagai umbi-umbian, dipagari langsung oleh perbukitan. Gunung Rumput menghampar tinggi dipacak matahari petang. “Di balik perbukitan itu, Malaysia,” Libertus mengucek matanya. “Kita punya adat, tapi tak punya tanah ulayat,” Libertus bicara kembali. Angin bertiup kencang, dan awan gelap seakan menutup semua lapisan langit petang 28 Agustus 2023.
“Secara masif, tanah di Kalimantan ini terjual dengan berbagai cara. Masa sawit sedang berlangsung. Dulu sebelumnya, masa karet. Orang masih punya waktu di rumah, bercerita dengan anak. Tapi, sekarang, masyarakat menjadi buruh di tanah sendiri,” kata Ignasius Anggoro, peneliti sekaligus manager di lembaga Wahana Visi Indonesia yang telah 16 tahun mendampingi dan menyoroti persoalan-persoalan yang muncul di kawasan ini, terutama kekerasan pada anak.
Adat berubah, sebagaimana waktu. Perkampungan berubah, pembangunan masuk, perkebunan luas tercipta, pendidikan kian mudah diakses. Namun janggalnya, masalah baru datang membarenginya. Sebagaimana kata Fatma, anak-anak terpisah dari orang tua mereka yang sibuk bekerja. Tidak sedikit warga yang bekerja ke negeri tetangga, termasuk anak yang masih usia sekolah. Untuk mencegah hal janggal tersebut berlarut-larut, desa-desa di kecamatan Sajingan Besar menerbitkan peraturan desa untuk membatasi tingkat kekerasan, pernikahan terlalu dini, juga pendidikan yang kian merosot. Pelarangan demi pelarangan digalakkan, sampai stiker-stiker ajakan supaya tidak cepat menikah menempel di dinding, di pintu-pintu rumah warga.
Di rumah kayunya yang gerah dan hanya televisi sebagai satu-satunya perabotan modern yang ada di ruang tamunya, Rita duduk di samping karung-karung beras. “Tahun kemaren, tiga orang di kampung ini yang menjadi korban kekerasan seksual,” katanya. Bersama dampingan dari Wahana Visi Indonesia, Rita berusaha mendampingi korban kekerasan ke polisi. Sebelumnya, kata Rita, hal-hal seperti ini jarang dilaporkan. Ia bersikukuh supaya pelaku kekerasan seksual dipenjarakan dengan melaporkannya pada polisi. Dan untuk tindakannya itu, Rita kerap mendapat tekanan. Rita hanya seorang petani, suaminya petani, anak-anaknya masih sekolah.
Dari tempat Rita, saya pindah ke sebuah kafe di dekat kantor Bupati. Sembari minum kopi bersama Boni, Ketua Dewan Adat Dayak di Kabupaten Sambas, saya bertanya akan persoalan yang terjadi belakangan. Berbeda dengan Libertus dan pemuka-pemuka adat lainnya, Boni adalah seorang dokter. Sebagai dokter, ia tentu lebih paham dengan masalah-masalah yang terjadi belakangan yang tidak semata dilihat dari kaca mata adat. Apakah peraturan desa, ataukah peraturan adat itu berguna untuk menurunkan jumlah kekerasan yang terjadi?
“Pelecehan didenda 100 tahil. Itu baru pelecehan. Satu tahil itu setara Rp. 175.000. Zaman berubah. Tempayan, hewan buruan yang biasanya sebagai denda semua akan diganti dengan uang. Ini kadang dianggap komersil, tapi sejauh ini efektif,” kata Boni. Ia menyeruput minumannya.
“Beginilah. Pertahanan adat makin rapuh. Lahan terjual, kekerasan muncul. Lahan dan hak ulayat bermasalah. Asal HGU keluar, semua bisa dirampas,” dokter Boni mengeluh.
Tak jauh dari rumah Rita, tak jauh dari kafe tempat saya berbincang dengan dokter Boni, gapura perbatasan berdiri megah di desa Aruk. Patung burung garuda berdiri besar, anak-anak yang berlarian di ujung gapura, anjing kampung berjalan gontai. Dari perkampungan, negara tetangga terlalu dekat dijangkau ketimbang ibu kota.
Sekali lagi, tidak semata tanah dan penguasaan lahan yang menjadi sengketa, namun juga kasus kekerasan seksual dan kekerasan pada anak. Pada tahun-tahun terakhir dampingan Wahana Visi Indonesia di tapal batas Indonesia ini, kata Anggoro, mendorong supaya terlaksananya hal-hal kongkret seperti peraturan desa dan adat—salah satunya aturan adat yang selama ini hanya bersipat lisan, telah dituliskan.
“Seberang sana, itu Kuching. Di Malaysia, harga kebutuhan lebih murah, gaji lebih besar dari di Indonesia,” kata Marcus, penjaga perbatasan yang tiap sebentar tersenyum ramah. Kulitnya yang kuning memerah diterpa matahari petang, dan ia selelu tersenyum tiap kali selesai bicara membuat matanya kian menyipit. Kami berbincang saat langit petang mulai memerah. Sebentar lagi kegelapan akan datang.
https://kumparan.com/fatrismf/di-tapal-batas-21EL3wLodcq/full