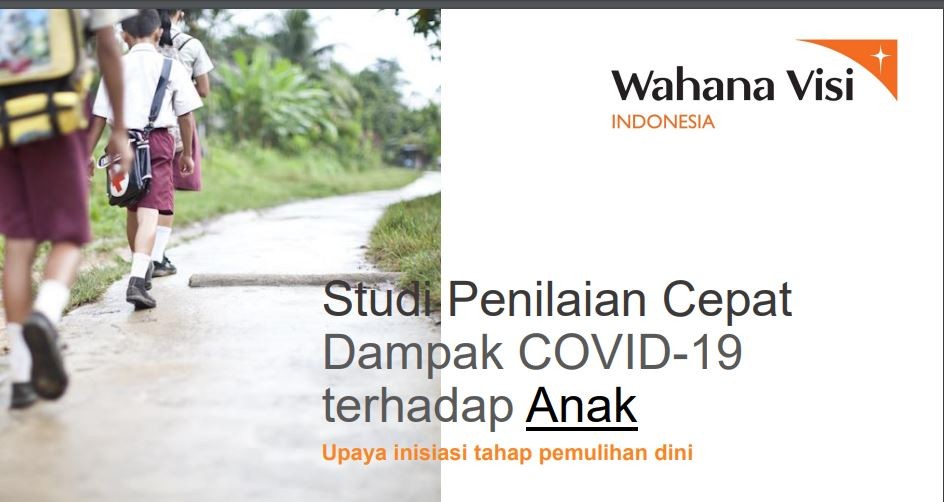Kerentanan Berlapis Anak Perempuan Belum Jadi Perhatian Pengadilan

Sosok AG (15), anak berkonflik dengan hukum dalam perkara penganiayaan berat terhadap Cristalino David Ozora (17), selama beberapa bulan terakhir menjadi sorotan publik. Sejak kasus tersebut bergulir hingga persidangan, tidak hanya di media sosial, perempuan remaja ini pun menjadi salah satu pusat perhatian pemberitaan media massa.
Sebagaimana diberitakan, AG dalam putusan hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, yang dibacakan hampir sebulan yang lalu, Senin (10/4/2023), divonis bersalah dan dihukum pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan vonis untuk AG lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut hukuman penjara selama 4 tahun.
Hakim menilai AG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menganiaya dengan terencana lebih dahulu sebagaimana yang didakwakan. Sepekan setelah putusan pengadilan tingkat pertama, Senin (17/4/2023), penasihat hukum dan jaksa penuntut umum menyampaikan pernyataan banding.
Sepuluh hari kemudian, Kamis (27/4/2023), hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta membacakan putusan banding, yang kembali menghukum AG dengan pidana penjara 3 tahun 6 bulan, atas sama dengan putusan PN Jakarta Selatan.
Para aktivis perlindungan anak menegaskan kekerasan terhadap anak tidak bisa ditoleransi, termasuk penganiyaan terhadap David. Karena itu, perlindungan terhadap anak harus menjadi perhatian bersama. Demikian juga proses pengadilan terhadap anak-anak hendaknya tidak mengabaikan kepentingan anak.
Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Dian Sasmita, menilai vonis hakim PT DKI yang menguatkan putusan PN Jakarta Selatan menunjukkan putusan banding belum memasukkan analisis Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (Bapas) terhadap kondisi anak, keluarga, dan lingkungan sosialnya.
Penelitian kemasyarakatan dari Bapas jadi kekhususan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang memakai pendekatan keadilan restoratif. ”Pendekatan ini tidak untuk membebaskan anak dari tanggung jawab atas kesalahannya. Namun, mendukung pembinaan anak agar bertanggung jawab atas kesalahannya,” tegas Dian.
Maka, seharusnya rekomendasi Litmas Bapas menjadi salah satu aspek penting menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam SPPA. Kehadiran PK Bapas dan Litmas dinilai vital untuk membantu penegak hukum menerapkan keadilan restoratif sehingga hakim wajib mempertimbangkan Litmas Bapas sebelum memberikan putusan terhadap perkara anak.
”Pemenjaraan anak merupakan upaya terakhir dan sesingkat mungkin. Dan hak-hak dasar anak lainnya, selain perampasaan kebebasaan, harus tetap dipenuhi oleh negara, seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain,” kata Dian.
Adapun Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menghormati putusan hakim banding tersebut. Untuk memastikan keadilan dan kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagai korban dapat dipenuhi, pihak yang beperkara masih dapat melakukan upaya hukum lain, yakni kasasi dan peninjauan kembali.
Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA Nahar menilai upaya hukum penting bagi anak yang berkonflik hukum untuk memastikan pemenjaraan hanya sebagai upaya terakhir dan dilaksanakan dalam waktu yang paling singkat.
Selain itu, untuk memperoleh keadilan dalam proses pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak, termasuk diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
Viktimisasi berulang
Kriminolog FISIP Universitas Indonesia, Mamik Sri Supatmi, menilai, putusan pengadilan negeri yang dikuatkan putusan banding sangat tidak sesuai prinsip kepentingan terbaik anak, khususnya terhadap anak perempuan yang dianggap melanggar hukum.
”Proses peradilan dan putusan juga membuktikan kegagalan negara memahami kerentanan berlapis yang dialami anak perempuan dan abai terhadap dampak pemenjaraan yang berbeda—lebih menderitakan—bagi anak perempuan,” ujar Mamik.
AG juga merupakan korban, yang dalam pengadilan sebelumnya justru mengalami viktimisasi kembali. Mamik menegaskan, pengadilan melanggar hak atas privasi dan memperlakukan pengalaman kekerasan seksual anak perempuan (dalam hal ini AG) sebagai instrumen yang makin mendiskreditkan.
”Tak hanya itu, pengadilan menyangkal penderitaan AG sebagai korban dari publik yang seksis dan misogini, selain korban dari pacarnya, Mario,” kata Mamik.
Sejak awal proses peradilan anak terhadap AG sudah melenceng jauh dari prinsip perlindungan anak sebagaimana dalam prinsip-prinsip dalam Beijing Rules (Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice).
Adapun prinsip-prinsip dalam Beijing Rules merupakan peraturan-peraturan minimum standar PBB mengenai administrasi peradilan bagi anak, Konvensi Hak Anak, dan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) serta perlakuan terhadap anak perempuan (merujuk pada Bangkok Rules).
”Kebencian publik terhadap anak perempuan lebih kental mendominasi proses peradilan terhadap AG ketimbang proses yang berpihak pada kepentingan terbaik anak dan perlindungan khusus kepada anak perempuan-korban kekerasan seksual,” ujar Mamik.
Dengan demikian, SPPA gagal memahami viktimisasi berlapis dan kekerasan berbasis jender yang dialami AG. tetapi malah meneguhkan respons reaktif-punitif yang didasari oleh kemarahan yang membabi buta dan seksis terhadap anak perempuan.
Putusan banding pun mendapat kritik tajam dari Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (Aliansi PKTA). Aliansi yang terdiri dari Yayasan Sayangi Tunas Cilik, Wahana Visi Indonesia, Childfund Indonesia, Plan International Indonesia, serta Institute for Criminal Justice Reform, dan ICT Watch pun bersuara.
Mereka meminta agar Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung aktif memberi perhatian atas persidangan kasus anak berkonflik dengan hukum tersebut, karena ada dugaan pelanggaran dengan tidak mempertimbangkan seluruh berkas banding. Pemeriksaan kasus tersebut seharusnya proporsional, dan kepentingan terbaik bagi anak harus diutamakan.
Para aktivis perlindungan anak menilai asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya murah, sejatinya tidak mengesampingkan prinsip peradilan yang adil (fair trial), apalagi dalam kasus tersebut terkait dengan anak-anak.
Karena itu, Aliansi PKTA mempertanyakan proses putusan banding dari PT DKI Jakarta yang dinilai terlalu terburu-buru. Sebab, berkas memori banding secara resmi baru diterima hakim, sehari sebelum putusan dibacakan.
Hal itu dibenarkan Manggata Toding Alo, penasihan hukum AG, bahwa pihaknya baru menyerahkan berkas memori banding ke PN Jakarta Selatan pada 26 April 2023 sekitar pukul 15.00 WIB. ”Sekitar pukul 15.30, jaksa juga memasukkan berkas. Kami sama-sama memasukkan berkas hari itu,” kata Manggata.
”Artinya, hakim PT DKI Jakarta hanya menggunakan waktu kurang dari 24 jam dalam mempertimbangkan dan menjalankan prosedur dalam menjatuhkan putusan banding. Pemeriksaan kasus itu seharusnya proporsional, kepentingan terbaik bagi anak harus diutamakan,” ujar Erasmus Napitulu, Ketua Presidium PKTA, Minggu (30/4/2023).
Padahal, seharusnya majelis hakim di tingkat banding membutuhkan waktu yang banyak untuk memelajari kasus tersebut kemudian mempertimbangkannya saat menjatuhkan putusan.
”Apabila praktik penjatuhan putusan yang terburu-buru dinormalisasi, maka upaya hukum banding tidak akan memberikan ruang keadilan, tidak hanya untuk anak AG juga pihak lain, terutama korban dan kelompok rentan,” ujar Erasmus.
Putusan hakim PT DKI Jakarta terhadap AG dinilai mengesampingkan berbagai prosedur pemeriksaan banding yang diperlukan untuk memastikan adanya ruang keadilan bagi para pihak yang beperkara. ”Asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan tak boleh membatasi kewajiban hakim untuk memeriksa substansi perkara,” ujar Erasmus.
Aliansi PKTA pun menyampaikan sejumlah catatan. Hakim banding dinilai mengabaikan kesempatan untuk mendengarkan pendapat kedua belah pihak secara seimbang, sebagaimana asas audi et lateram partem (hakim harus mendengar dua belah pihak secara seimbang).
Hakim banding juga dinilai mengabaikan fakta bahwa AG juga merupakan korban tindak pidana. Secara substansi, putusan PN sebelumnya memaparkan kronologi yang menyatakan AG berhubungan seksual dengan salah satu pelaku dewasa sebanyak lima kali.
Seharusnya hakim mempertimbangkan perbuatan hubungan seksual orang dewasa dengan anak sebagai bagian dari potensi adanya relasi kuasa dengan pelaku utama, dan bahkan potensi pelanggaran pidana.
Hal itu sejalan dengan Paraturan MA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta UU Perlindungan Anak.
Manggata menyatakan, pada memori banding, penasihat hukum juga menyampaikan rasa kekecewaan terhadap ketidakcermatan serta tindakan pengabaian hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan dan mengambil keputusan, karena tidak mempertimbangkan hasil Litmas Bapas, hasil pemeriksaan psikologi forensik, dan laporan sosial.
Padahal, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan tersebut, sudah dapat diketahui bahwa AG memiliki ketidaksempurnaan kejiwaan. ”Kami hanya berharap hukum secara adil,” ungkapnya menegaskan.
”Hasil psikologi forensik penting untuk menilai perilaku seseorang. Jadi, kami tidak meminta hukuman klien kami direndahkan atau dikurangi, tetapi mohon hakim pelajari penelitian yang disampaikan,” kata Manggata.
Proses peradilan terhadap AG masih terus berlanjut. Tentu publik masih harus menunggu hasil akhirya seperti apa, hingga putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Harapannya, pengadilan tidak mengabaikan kepentingan terbaik bagi anak.